Gurun Puisi WS Rendra
August 15, 2014 § Leave a comment
Rendra menerbitkan buku puisi terakhir pada tahun 1997. Pada saat itu, Yayasan Obor milik Mochtar Lubis lah yang menelurkan kumpulan puisi Mencari Bapa dan Perjalanan Bu Aminah sebagai karya terakhir Willybrordus Surendra Bhawana Rendra Brotoatmojo. Ya, itulah nama lengkap dari Willy Sulaiman Rendra. Nama terakhir digunakan setelah Rendra masuk Islam pada tahun 1970.
Rendra, dikenal sebagai penyair pamflet. Penyair Pamflet yang berarti karena puisinya bisa berada di mana saja, tertulis apa saja, merekam apa saja. Atau mungkin disebut Penyair Pamflet karena diasosiasikan dengan buku puisinya yang pernah kena bredel y: Pamflet Penyair. Untungnya A. Teeuw berhasil menyelamatkan, sekaligus menerjemahkan, semesta puisi tersebut ke dalam Bahasa Belanda dan diedarkan di sana. Di Indonesia, judul Pamflet Penyair bermetamorfosis menjadi Potret Pembangunan dalam Puisi, yang lolos dari sayatan sensor dan beredar pada tahun 1980.
Laku hidup Rendra dititah lewat buku filsafat dan sastra sejak bangku SMA. Melalui kaca perspektif yang beragam, Rendra kemudian menyuji puisi-puisinya. Puisi Rendra hampir selalu menyergap nuansa yang berada di luar dirinya, namun ada juga perenungan-perenungan tentang Tuhan yang berasal dari dalam dirinya.
Tuhan, adalah sosok misterius yang dipertanyakan oleh Rendra. Pada sajaknya “Kupanggil namamu” (ya, dengan mu kecil karena tidak sedang berbicara tentang Tuhan), Rendra menyebut Tuhan adalah seniman tak terduga yang selalu sebagai sediakala, (dan) hanya memedulikan hal yang besar saja. Nada protes jelas nyaring dikeluarkan dalam sajak ini. Dalam sajak tersebut, Rendra nampak gundah, tak acuh, menceraikan diri. Namun, di sajak lain, “Gumamku, ya Allah”, Rendra justru mentransendenkan Tuhan ke dalam dirinya. Ia berkata “Angin dan langit dalam diriku, adalah bayangan rahasia kehadiranmu, Ya Allah”. Nampaknya, rentang waktu 12 tahun jeda telah membuat proyeksi Rendra akan Tuhan tampil dalam wujud yang berbeda.
Sajak “Gumamku, Ya Allah” adalah sajak pertama dari kumpulan puisi Rendra yang (mungkin) benar-benar terakhir. Kumpulan puisi ini berjudul Doa untuk Anak Cucu. Doa untuk Anak Cucu berisi puisi-puisi Rendra yang belum pernah dibukukan selama hidupnya. Puisi yang dibukukan adalah puisi yang lahir antara tahun 1983 dan 2009.
Doa untuk Anak Cucu seperti mengais puisi-puisi Rendra yang “menghilang” akibat kesibukan Rendra di Film dan Teater. Walhasil, tidak akan ditemukan tema yang khas dari keseluruhan sajak yang terhampar di sini. Buku Doa untuk Anak Cucu terlihat sekedar menampilkan rupa khas sajak-sajak Rendra yang makin lugas dan tanpa basa-basi.
Saya tertarik pada puisi “Tuhan, Aku Cinta pada-Mu” yang ditulis di bulan-bulan terakhir Rendra. Di senjanya, Rendra seperti benar-benar leleh dari kristal kehidupan yang sudah dipahatnya. “Aku ingin kembali ke jalan alam// Aku ingin meningkatkan pengabdian kepada Allah” tulisnya di puisi yang bertarikh 31 Juli 2009 tersebut. Rendra seakan mafhum kepada penyerahan diri setelah bertahun-tahun bergulat dengan penyakit, lalu kembali kepada Tuhan, kepada agamanya yang dia sebut sebagai kemah para pengembara.
Pengembaraan mengenal jejak dan jarak. Kata-kata yang dikembarakan Rendra sendiri merupa berbagai macam jejak dan jarak nuansa. Pada awal-awal kepenulisannya, Rendra cenderung menulis secara khayali dan penuh metafora. Namun semakin lama, sajaknya berubah sehingga terdengar lebih lugas. Dalam doa untuk anak cucu, sajak “Gumamku, Ya Allah” sangat berbeda dengan saja “Doa” meskipun menyuarakan hal yang sama. “Gumamku, ya Alloh” masih menampilkan kata-kata magis seperti “Semua manusia sama tidak tahu dan sama rindu” terhadap apa yang Rendra maksud sebagai “musafir-musafir yang senantiasa mengembara. Umat Manusia tak ada yang juara”. Rendra menceritakan kerinduan kepada Tuhan yang terbersit dari jiwa manusia yang mengembara dalam hidupnya dan terombang-ambing. Hal itu kemudian terkait dengan bayangan rahasia kehadirian Allah di awal sajak ini. Rendra memotret keterpasrahan dalam ombang-ambing kehidupan. Dalam sajak doa, Rendra lebih lugas memotret keterpasrahan itu dengan lugas: “Allah menatap hati. Manusia menatap raga. Hamba bersujud kepada-Mu, ya Allah! Karena hidupku, karena matiku.”
Sudah pasti terjadi juga dismilaritas akan bahasa dan tema dalam sajak-sajak di buku ini. Sajak paling tua dalam buku ini adalah “Hak Oposisi” yang bertarikh 10 Oktober 1971, sedangkan yang paling muda adalah “Tuhan, Aku Cinta pada-Mu” yang lahir pada 31 Juli 2009. Ruang usia yang berjeda hampir 40 tahun mengakibatkan dismilaritas yang kentara.
Rendra konsisten menggeledah situasi sosial di sekitarnya untuk membuka simpul-simpul kemuraman pemerintahan dan kemanusiaan. Sajak keras mengenai kerusuhan yang mengiringi reformasi Mei 1998 misalnya. Ia menuliskan kegundahannya akan kekerasan yang terjadi pada saat itu. Rendra memulai sajaknya dengan “Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja” yang mengindikasikan keterkaitan reformasi tersebut dengan periode gelap “raja” yaitu presiden. Sajak itu diakhiri dengan pedih juga: “Air mata mengalir dari sajakku ini”.
Detak kemuraman itu juga tercermin pada sajak-sajaknya yang lain seperti “Kesaksian Akhir Abad dengan larik: “Kejahatan kasatmata tertawa tanpa pengadilan. Kekuasaan kekerasan berak dan berdahak di atas bendera kebangsaan”, “Perempuan yang Tergusur”, ‘Maskumambang”, dan “Politisi itu Adalah”.
Rendra, melalui sajak-sajaknya, seperti memendam kegundahan yang tidak bertepi mengenai lini-lini zaman yang terus bergerak. Pergerakan zaman yang seakan meninggalkan ketidakadilan sebagai pekerjaan rumah yang berakhir sebagai tanda tanya. Rendra mengkhawatirkan pekerjaan rumah ini akhirnya masih dalam kondisi yang menganga, lalu diwariskan kepada anak cucu. Atas dasar ini pula penyebab “Untuk Anak Cucu” dinukil dan diletakkan sebagai judul buku.
Doa untuk anak cucu, adalah akhir dari gurun puisi WS Rendra. Sudah 17 tahun kita absen membaca dan menziarahi kata-kata yang diwariskan Rendra. Pada tenggang waktu tersebut, dahaga akan puisi Rendra menjadi gurun yang menanti hujan. Akhirnya, hujan itu datang dalam bentuk doa untuk anak cucu. Hujan yang turun ini cukup menggembirakan, menyejukkan, walau pada akhirnya kita akan merasakan gurun puisi Rendra yang mungkin tidak akan berkesudahan. Kecuali jika ada puisi yang memang belum tampil dan bersuara serta menjelma sebagai hujan kembali.
Rendra berperang dengan kata-katanya dan sudah tunai perangnya melawan, mengutip Agus Noor, zaman yang penuh dengan godaan kesementaraan. Tapi, suatu hal yang saya percaya bahwa kata-kata memiliki sukma yang tak terpahami dan bisa menjadi pelita bagi “anak cucu” untuk melawan godaan kesementaraan di zamannya sendiri. Ya, kata-kata bisa menjadi energi dalam menjawab teka-teki nasib masing-masing yang acap diperjuangkan. Seperti katamu jua Rendra: perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.
Mencintai adalah sebuah pekerjaan
August 11, 2014 § Leave a comment
resensi buku The Art of Loving – Erich Fromm
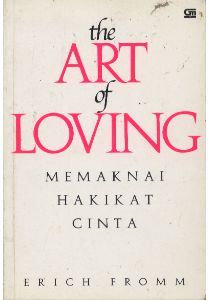
Love is a verb. Frase ini menjadi sebuah dekonstruksi yang tersaji di awal saya membaca buku ini. Cinta, bukan sebuah benda. Cinta, bukan sebuah sifat. Ia adalah sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan berarti membutuhkan subjek dan objek. Subjek melakukan sesuatu sehingga objek meniadakan gemingnya. Ia bergerak, atau ia tergerak. Artinya, permasalahan mengenai cinta dapat menarik siapa saja ke dalam pusarannya. Jadi, jika Anda berpikir bahwa cinta adalah sebuah benda atau keadaan, buku ini akan meruntuhkan bangunan pemikiran anda menjadi puing belaka.
The Art of Loving adalah buku karya Erich Fromm, seorang yang rajin menggerimiskan kesinisannya terhadap zaman. Fromm dikenal sebagai seorang filsuf, psikologis dan psikoanalis yang bergulat dalam roda kemanusiaan sebagai bidangnya. Buku ini didengungkan sebagai karya terbaik dari Fromm, walau Saya lebih memandangnya sebagai karya Fromm yang paling populer. Fromm, lahir dan besar di Jerman. Ia menjadi saksi dari kesombongan manusia yang memegang senjata. Perang Dunia I menjadi pergolakan yang sangat mempengaruhi kepribadian para warga negara Jerman saat itu.
Potret yang dibingkai oleh Fromm adalah cinta dalam arti luas. Cinta yang ternyata adalah sebuah semesta di mana keseluruhan elemennya saling menguatkan sekaligus saling meniadakan. Fromm membagi cinta berdasarkan objeknya: cinta sesama, cinta diri, cinta erotis, cinta ibu, dan cinta kepada Tuhan. Setiap elemen hanya berbeda dalam objek, tapi Fromm menarik garis di mana objek itu masih berada dalam lingkaran yang sama.
Cinta, yang kita kenal sekarang dipahat dari budaya kontemporer yang sudah berjalan sejak awal abad 20: budaya kapitalisme. Kapitalisme berarti pasar yang terdiri dari penjual dan pembeli. Cinta, dalam budaya kapitalisme, tak ubahnya komoditas yang diperjualbelikan dalam tatanan pasar. Ia taat pada pemberlakuan hukum permintaan dan penawaran. Tiap orang berlomba menawarkan “paket kepribadian” yang dimilikinya untuk mendapatkan “paket kepribadian” yang dimiliki orang lain. Masyarakat secara bersama-sama menjadi organisme egosentris yang teralienasi serta berorientasi pada konsumsi. Fromm menulis; “manusia modern teralienasi dari dirinya, sesama, dan alam. Ia telah berubah menjadi komoditas, menghayati kekuatan hidupnya sebagai investasi yang harus memberikan keutungan maksimal yang diperoleh dari kondisi pasar yang ada.”
Dengan pasar sebagai titik tolak cinta. karakter masyarakat pun berubah. Ia bergeser menjadi, mengutip Fromm lagi, pengisap yang selalu penuh harapan dan selalu kecewa. Oleh karena itu, selera Pasar “Cinta” itu pun berubah-ubah. Jika pada awal abad ke-20, gadis yang menarik adalah mereka yang suka minum-minum, merokok, dan dansa-dansi, maka pada waktu sekarang pasar lebih memihak gadis yang malu-malu kucing dan sayang pada keluarga. Demikian juga dengan lelaki. Kini, pasar lebih memuja lelaki yang suka bergaul dan toleran, menggeser fenomena lelaki yang dipuja karena ambisius dan agresivitasnya.
Begitu volatilitasnya pasar “cinta” atau kepribadian ini, maka peserta yang terjun dan berinteraksi di dalam kumparan ini digiring secara tidak sadar ke dalam kekecewaan. Penilaian terhadap cinta menjadi sesuatu yang dipersyaratkan, dan manusia, pada satu titik waktu, akan tidak merasa puas atas pertukaran paket kepribadian yang telah dilakukan.
Lalu kenapa manusia harus bisa memeluk cinta dalam sayap-sayap kehidupannya? Fromm memaknakan cinta sebagai jawaban atas eksistensi manusia. Manusia sadar ketika lahir, bahwa dirinya hadir dalam sebuah entitas yang terpisah, berumur pendek, tidak memiliki kehendak atas kematiannya, serta keragu-raguan atas semua probabilitas yang menghampar di hadapannya. Keterpisahan yang dituntun oleh ketidakpastian serta keragu-raguan, akan menyeret manusia dalam padang kegelisahan yang mendalam. Cinta, menurut Fromm, terlukis sebagai jalan keluar bagi manusia untuk mengatasi keterpisahannya. Cinta adalah media agar manusia tidak terjebak ke dalam kelenyapan dirinya dari dunia, akibat dari kegagalan untuk mengatasi isolasi dirinya.
Interaksi antar manusia kemudian berkembang dengan adanya konformitas, yaitu penyesuaian sikap dan perilaku. Penyatuan dengan orang lain demi menghilangkan kemungkinan kesendiriannya membuat manusia melakukan tawar menawar untuk mengikuti kesepahaman umum, kebiasaan, pola-pola yang dibuat kelompok semata-mata agar mereka tidak merasa tersisih dan sendirian, dan kemudian lenyap dari lingkaran sosialnya.
Fromm dalam buku ini mengetengahkan sikap bahwa ia memandang konformitas dalam hal penyatuan atas lawan dari keterasingan tidak melulu diidentifikasikan sebagai cinta. Fromm menulis bahwa apabila dalam suatu penyatuan terdapat submission atau domination, maka hal tersebut bukanlah cinta. Pribadi yang tunduk (submission) keluar dari perasaan isolasinya dengan menjadikan dirinya sebagai bagian dari pribadi lain yang menjadi daya hidupnya. Bagi pribadi jenis ini, dirinya bukan siapa-siapa, minor, cenderung masokis. Lawannya adalah pribadi yang memiliki sifat dominasi. Pribadi jenis ini keluar dari keterpenjaraaannya dengan membuat pribadi lain sebagai bagian dirinya. Ia adalah sosok yang sadistis, egosentris, dan narsis.
Cinta, adalah ketika keduanya melakukan peleburan tanpa integritas. Dalam soal ini, Fromm sendiri berujar “Cinta membuat dirinya mengatasi perasaan isolasi dan keterpisahan, namun tetap memungkinkan dirinya menjadi dirinya sendiri. Dalam cinta terdapat paradoks: dua insan menjadi satu, namun tetap dua”
Dalam persoalan eksistensial manusia, hal ini menjadi penting untuk dipahami. Dengan adanya peleburan tanpa integritas, manusia bisa mempertahankan sifat-sifatnya dan menolak mekanisme pasar yang terlalu cepat. Fromm menyentil untuk tidak terlibat dalam cinta yang semu terkait dengan mekanisme pasar. Cinta yang semu adalah keadaan di mana ia menyerahkan dirinya kepada sebuah mekanisme proyektif, yang menganggap sebuah fantasi tertentu adalah titik ideal di mana hal tersebut tidak dialami di sini dan sekarang. Akhirnya, hubungan cinta hanya serupa kegiatan saling proyeksi antara kedua belah pihak yang tidak berkesudahan.
Cinta dalam perspektif buku ini adalah mengenai sebuah pemberian, bukan penerimaan. The Art of Loving menjelaskan bahwa cinta yang hakiki adalah sebuah pemberian diri. Ia tidak merelakan hidupnya sebagai korban yang akhirnya tunduk pada submisif tertentu. Hal yang direlakan adalah apa yang hidup di dalam dirinya; kebahagiaan, minat, pemahaman, pengetahuan, kejenakaan, dan kesedihannya pada orang lain. Ia memperkaya orang lain, sekaligus memperkaya diri sendiri. Di sisi ini, manusia merestorasi kata-kata yang pernah diutarakan Chris McCandles: “Happiness only real when shared”.
The Art of Loving memberikan sebuah definisi cinta ala Timur. Cinta adalah perhatian aktif pada kehidupan dari apa yang kita cintai. Oleh karena itu, Fromm memegang teguh kenyataan bahwa daripada manusia sibuk melakukan proyeksi keinginannya untuk dicintai (yang selalu gagal), manusia lebih baik melakukan pekerjaan mencintai. Manusia harus bisa menghindarkan diri untuk menjadi komoditas dengan menjadikan atribut dalam dirinya sebagai sebuah nilai takar untuk meletakkan posisi diri di pasar kepribadian. Berlakulah, karena mencintai adalah sebuah pekerjaan. Kebahagiaan atas cinta lahir apabila pemberian yang dilakukan ditujukan untuk melestarikan kehidupan. Cinta bukan kebutaan pada realitas, namun menjadikan realitas sebagai daya untuk, mengutip Eckhart, mencintai semua dengan sama, termasuk diri sendiri. Dan dengan cara itu manusia dapat mencintai mereka sebagai satu pribadi dan pribadi itu adalah Tuhan dan Manusia.
Menertawakan Surat Orang-Orang Pintar
July 17, 2014 § Leave a comment
July 14, 2014 at 1:42am
Sebelum membaca tulisan ini jauh ke bawah, saya ingin coba perkenalkan diri saya dulu. Saya bukan aktifis yang terkenal dizaman saya, bukan pula teladan bagi banyak orang. Saya adalah seorang alumnus yang sedang tertawa terbahak-bahak membaca surat-menyurat “dua senior” saya di sekolah saya dahulu.
Sekolah saya ini agak unik memang. Orang yang lebih tua bisa saja masih sekolah, saya yang masih muda dan imut ini sudah lulus dari sekolah. Bukan berarti saya pintar ya. Saya hanya menjalankan sebuah proses yang saya sebut sebagai penghambaan pada Yang Kuasa.
Sekarang kita coba melangkah “sedikit” lebih maju. Kenapa tulisan ini saya tulis?
Tujuan saya tentu bukan sedang “membodoh-bodohkan” dua senior saya tadi. Bukan pula untuk ikut campur dalam urusan surat cinta mereka. Cinta mereka biarkan bersemi. Saya hanya tertarik dengan logika semprul yang mereka ajukan sebagai pembelaan diri mereka.
Pada surat pertama, si penulis menentang SARA. Saya pinjam istilah penulis sebagai “pendikotomian mahasiswa menjadi dua sisi”. Muslim-Non Muslim, Lama-Baru, Akuntansi-Pajak, dsb.
Pada awalnya, saya suka dengan pembukaan surat cinta nya. Tapi yang saya lihat, argumentasi penulis tidak lebih daripada logika anti-negasi dari isu yang berkembang. Bila penulis mengkritisi isu-isu yang “menjangkit” mahasiswa dengan persoalan agama, ia pun berusaha menegasikan isu tersebut. SARA itu negasi kesamaan hak untuk dipilih, alasan anti-SARA pula merupakan anti-negasi dari negasi kesamaan untuk dipilih. Usaha yang bagus tapi sesat!
Sesat, kata saya. Sesat karena menggunakan argumentasi Pancasila sebagai pendukung anti-SARA. Jika kita telisik Pancasila kita dalam sekali, sila pertama contohnya, kita akan temukan bahwa Ketuhanan yang dimaksud pada sila pertama adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang lapang dan toleran, bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan.
Sila ini jelas menegaskan etis-religius bangsa ini. Maka suatu kewajiban bagi setiap umat agama “berproses” berdasarkan agamanya masing-masing. Tapi perlu diingat, pada saat yang sama, negara ini tidak mewakili agama tertentu tapi menfasilitasi, melindungi dan menjamin keamanannya.
Belum lagi, tanpa persetujaun Ki Bagoes Hadikusumo, Kasman Singodimejo dan Teuku Moh Hassan, Pancasila kita tidak akan menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Dan mereka bertiga menyetujui perihal itu sebagai emergency exit dengan pemaknaan bahwa Yang Maha Esa itu berarti Allah. Ini semacam kompromi agar sahabat-sahabat dari gereja Indonesia Timur bisa menerima kemerdekaan Indonesia secara bersama-sama.
Nah, bila ada anjuran untuk mengikuti ajaran Islam secara kaffah dan ditentang oleh penulis dengan logika Pramoedya Ananta Toer (sastrawan pendukung Komunis), saya sungguh tidak setuju. Konstitusi kita “memerintahkan” kita untuk mengikuti anjuran agama dengan kaffah.
Bila penulis pertama bicara program dan visi misi, lanjutkan. Tapi bila penulis seolah-olah menegasikan pilihan berdasarkan agama dengan pemaknaan Pancasila yang keliru, itu menggelikan.
Sahabat pembaca bisa temukan penjelasan saya di buku Negara Paripurna tulisan Dr. Yudi Latief atau publikasi resmi tentang 4 Pilar Kebangsaan dari MPR RI. Penjelasan ini juga berlaku untuk sila ke 2 hingga ke 5 karena berdasarkan sifat hierarkis dan piramidal Pancasila. Sila kedua dijiwai sila pertama, Sila ke 3 dijiwai sila pertama dan kedua, dsb.
Para Haters Penulis pertama jangan senang dulu dengan “penertawaan” saya pada penulis pertama.
Bila penulis pertama mengalami kesalahan filosofis dalam argumen nya, penulis kedua lebih menyedihkan lagi.
Perlu ditegaskan bahwa apa yang disampaikan penulis kedua mengenai An-nisa 144 tidak salah. Benar secara kutipan. Tapi salah secara pemahaman. Jelas sekali penulis masih sangat hijau dan tidak memahami Islam secara benar. Tulisan penulis jelas sebuah serangan yang ambisius untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya.
Jika kita bicara tentang pengangkatan Non Muslim sebagai pemimpin, kita bicara 3 bagian utama:
- Sebagai Wali Amanah (Kepemimpinan umum dan punya nilai keagamaan strategis, dapat mempengaruhi agama)
- Wazhoif Qiyadiyah
- Wilayat Madaniyah
Yang dimaksud wali amanah disini menurut ulama adalah kepemimpinan yang bersifat mutlak, yang dalam islam sering diidentikkan dengan Khilafah. Qiyas nya adalah ria’satuddaulah / Presiden / Perdana Menteri. Dalam hal ini, ulama sepakat umat islam dilarang memilih kepala negara seorang non muslim.
Sedangkan untuk Wazhoif Qiyadiyah, ini seperti pembantu presiden atau pembantu menteri. Dan Wilayat Madaniyah ini seperti pelaksana lapangan, pembantu umum, dsb. Ulama punya perbedaan pendapat pada bidang ini.
Perhatikan gabungan kata huruf tebal tersebut. KEPALA NEGARA. Suatu entitas yang memiliki kekuasaan atas umat. Bukan sebuah organisasi mahasiswa yang melempem, bukan pula organisasi mahasiswa yang hanya mengurusi 5000an mahasiswa. Bukan pula organisasi mahasiswa yang “mengurusi” agama mahasiswa. Kita bahkan tidak sedang bicara kepemimpinan di wilayah wali amanah. Bahkan Wazhoif Qiyadiyah pun tidak.
Jelasnya, memilih pemimpin non muslim itu sendiri, ada perbedaan pandangan oleh ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Yang tidak beralasan dengan surat Al Mumtahanah : 13. Yang boleh beralasan dengan dengan permintaan perlindungan oleh Rasulullah kepada Raja Kristen Najasyi Negus saat 116 orang muslim hijrah ke Ethiopia.
Ulama yang memperbolehkan menyatakan bahwa larangan “memilih pemimpin non muslim” tidak mutlak. Larangan ini hanya berlaku bagi kafir golongan yang memusuhi islam sebagaimana diterangkan dalam Al Mumtahanah 1-2, Al Maidah 57 dan An-nisa 89. Konteks ayat tersebut jelas larangan diberikan pada orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam.
Bila kita meminjam istilah Syeikh Ahmad Mustofa Al Maraghi, orang islam dilarang mengambil orang non muslim sebagai pemimpin atau sahabat setia bila:
- Mereka tidak segan-segan merusak dan mencelakakan orang islam
- Mereka menginginkan urusan dunia orang islam sulit
- Mereka menampakkan kebencian kepada islam melalui mulut mereka secara terang-terangan.
Sekali lagi, orang kafir yang jelas-jelas memusuhi islam. Bila tidak, diperkenankan untuk memilih. Tapi ini tidak berlaku untuk Wali Amanah (Kepala Negara/Legislatif yang membuat aturan dsb) ya. Itu mutlak diharamkan. Saya yakini bahwa saya sangat ragu bila ada calon yang sedang diserang penulis kedua sedang “memusuhi” islam. Saya kenal betul dengan calon non muslim tersebut. Karena itu saya bahkan memilih calon yang diserang penulis kedua sebagai Ketua SPEAK angkatan ke 7. SPEAK adalah sebuah organisasi mahasiswa yang bergerak dalam bidang gerakan integritas, Indonesia bersih dan anti korupsi.
Saya memilih beliau karena saya paham dengan agama saya. Karena saya memahami substansi nilai-nilai islam seperti yang saya jelaskan ini.
Maka jelas melalui tulisan ini saya menertawakan penulis kedua dengan sangat. Bila penulis pertama saya sebut menggelikan, maka penulis kedua ini sangat menyedihkan. Menggunakan pemahaman islam yang tidak tepat untuk menarik perhatian. Ujung-ujungnya Islam pula yang menjadi jelek. Islam pula yang “seperti tersalahkan”. Padahal itu akibat ketidakpahaman penulis dalam memahami nilai-nilai luhur keislaman yang indah ini.
Saya akhiri penertawaan saya malam ini dengan ceria. Sudah tengah malam ini, sudah saatnya kita menghadap Allah bukan dalam sholat malam bukan? Ayo Bangun! ^_^
Hormat saya,
Alumnus yang suka menertawakan kesokpintaran.
Riyan Al Fajri.
sumber:
Menjawab “Surat Terbuka Kepada Mahasiswa STAN”
July 17, 2014 § Leave a comment
Agama adalah candu. Begitu keyakinan kaum materialis-komunistis ketika melihat kenyataan bahwa agama telah menjadi alat pembenaran bagi penguasa negara theokrasi memeras habis kapital rakyatnya. Namun, pendapat itu tidak selamanya benar. Bagi sebagian orang, agama adalah obat. Oase di tengah padang pasir keserakahan manusia yang menjadikan benda sebagai landasan berpikir. Cahaya bagi kegelapan peradaban yang menjadikan pikiran manusia yang terbatas sebagai acuan kebenaran.
Dalam perjalanannya, agama selalu berdampingan dengan politik. Agama dan Politik seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pemilihan Umum Presiden 2014 tanggal 9 Juli lalu pun diwarnai isu-isu seputar agama. Antara Islam dan non-Islam. Antara Islam dan sekularis. Ternyata, geliat politik di perhelatan besar lima tahunan ini bergulir ke sebuah kampus bagi para abdi Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
Dalam pemilihan presiden mahasiswa tahun ini, warga STAN dihadapi oleh dua pilihan. Fandy, mahasiswa D-IV, semester 7, beragama Islam dan Gilang, mahasiswa D-IV, semester 9, beragama Katolik.
Merujuk tulisan Meidiawan Cesaria Syah berjudul “Surat Tebuka Kepada Mahasiswa STAN”, saya dapat membayangkan bahwa pertunjukan politik di sekolah kedinasan populer itu pun tidak sarat dari isu-isu agama. Di dalam tulisan beliau, isu yang menjadi pokok tulisan adalah sebuah pernyataan : bahwa sudah seharusnya muslim memilih kawan muslimnya, jangan yang non-muslim.
Apakah benar ini hanyalah sekedar isu dari sekelompok orang yang sudah tidak dapat berargumen untuk mencitrakan pemimpin pilihannya?
Sebelumnya, saya jabarkan dulu secara singkat tentang bagaimana seharusnya seorang muslim memandang agamanya dan mengkaitkannya dengan segala aspek kehidupan. Asy-Syahid Hasan Al-Bana pernah berkata mengenai agama ini, “Islam adalah negara dan tanah air, atau pemerintahan dan umat, ia adalah akhlak dan kekuatan, atau kasih sayang dan keadilan, ia adalah wawasan dan perundang-undangan, atau ilmu pengetahuan dan peradilan, ia adalah materi dan kekayaan, atau kerja dan penghasilan, ia adalah jihad dan dakwah, atau tentara dan fikrah, sebagaimana ia adalah akidah yang bersih dan ibadah yang benar.” Hasan Al-Bana menggambarkan wajah islam yang universal dan totalitas. Tidak mendikotomi permasalahan apapun di dunia ini dengan Islam. Bahwa, Islam tidak hanya mengurusi hal-hal berbau ritual belaka. Namun, Islam pun mengurusi hal besar yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak : politik.
Keyakinan Islam seperti di atas, hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki derajat iman. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya puncak kebenaran, acuan perkataan dan perbuatan. Bukankah Islam dalam bahasa arab bermakna penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Alah? Sehingga, adalah sebuah perkara yang jelas jika seorang muslim menjadikan kitabnya (Al-Quran) sebagai acuan kebenaran.
Pertanyaan bergulir menjadi, “Apakah kehendak Allah dalam menentukan pemimpin umat?”
Saya kutip dasar hukum yang nyata, yang berasal dari Tuhan yang saya dan anda yakini keberadaannya :
Hai, orang-orang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? (An-Nisa :144)
Meidiawan Cesaria, saya bertanya kepada nurani anda sebagai seorang muslim, apakah ayat ini hanyalah sebagai isu belaka yang dapat diacuhkan atas nama negara demokrasi? Apakah mereka yang menjadikan ayat ini sebagai acuan dalam memilih pemimpin masuk kedalam kategori pemilih sosiologis, yang anda tempatkan dibawah posisi pemilih rasional dan pemilih psikologis? Apakah mereka yang menjadikan ayat ini sebagai acuan adalah orang-orang yang tidak rasional? Saya, tidak satu pendapat dengan anda.
Kalau memang demokrasi membebaskan kita untuk berpendapat dan berkeyakinan, maka inilah pendapat dan keyakinan seorang muslim yang benar, yang tidak dapat dikacaukan dengan pemahaman apapun juga. Bahwa ini adalah pemahaman paling rasional bagi mereka yang tergerak hatinya ketika dipanggil oleh Tuhan sebagai “orang-orang yang beriman”.
Atas nama keberagaman bukan berarti setiap pemeluk beragama harus mengilangkan truth claimagama yang mereka miliki. Karena truth claim itulah yang membedakan satu agama dengan agama lainnya. Bayangkan semua orang menganggap tidak perlu lagi memegang truth claim dalam agamanya, maka untuk apa lagi ada agama di dunia ini?
Akhir kata, saya mengajak semua mahasiswa STAN yang bergama Islam, yang menyatakan diri loyal kepada Allah dan berlepas diri selainnya agar menjadikan kitabullah sebagai satu-satunya acuan dalam memilih pemimpin. Jangan pernah goyah oleh pendapat-pendapat mereka yang menjadikan demokrasi sebagai illah-illah pengganti Allah. Sungguh, Allah akan memenangkan kita jika berada di jalan yang lurus. Ingatlah cita-cita founding father kita sebelum mendapat protes dari tokoh agama dari Indonesia timur : ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Bali, 13 Juli 2014
Surat Terbuka kepada Mahasiswa STAN
July 13, 2014 § Leave a comment
Selamat Pagi, Mahasiswa!
Mahasiswa, Saya kira selalu berada dalam orbit pagi karena semangatnya, karena umurnya, dan karena kesiagaannya. Pagi di mana segala hal bermula. Pagi saat mata baru terbuka dan semangat ada di dalam dada. Sebelum senja merenta, sebelum malam menua.
Di awal surat ini, izinkan Saya mengutip paragraf yang ada di editorial Oven News Media Center STAN:
” Dalam teori pergerakan politik, terdapat beberapa tipe pemilih dalam mengambil pilihannya dalam pemilihan, yakni pemilih rasional, psikologis, dan sosiologis. Mahasiswa idealnya harus dapat memosisikan diri sebagai kaum intelektual. Mahasiswa adalah pemikir rasional, yaitu pemilih yang mampu berpikir secara kritis dan cerdas dalam menentukan pilihannya. Mahasiswa bukan pemilih psikologis yang memilih atas dasar kedekatan personal ataupun kesamaan kelompok. Mahasiswa juga bukan pemilih sosiologis, yaitu memilih atas dasar kesamaan SUKU, GOLONGAN, RAS, atau AGAMA. Pilihan kita akan menentukan arah perjalanan kampus ini setahun ke depan.”
Dari editorial Oven News ini, Saya menarik garis lurus kesimpulan bahwa mahasiswa sudah saatnya mampu memosisikan diri sebagai kaum intelektual, kaum yang terpelajar. Kaum yang menurut Pramoedya Ananta Toer harus “berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan”.
Mau tidak mau segala polemik yang menyergah baik dari rangkaian suara maupun teks dan kata-kata sudah menyelimuti atmosfer genta demokrasi di STAN ini. Adu program, adu misi, adu visi sudah wajar terjadi di permukaan. Tentunya juga adu idealisme dan ide-ide kreatif antar tim sukses berperang di bawah sana, nun di tempat jauh dan sunyi.
Calon Presiden Mahasiswa STAN tahun ini adalah dua orang yang sangat menarik perbedaannya. Salah satu calon adalah Fandy, mahasiswa DIV baru (semester 7) Akuntansi Reguler (lulus sekitar Oktober 2015), Jawa, dan Muslim. Sementara calon yang lain adalah Gilang, mahasiswa DIV lama (semester 9) Akuntansi Khusus (lulus sekitar Oktober 2015), Sunda, dan Katolik (Maaf saya tidak menyebutkan non muslim karena Agama Gilang juga bernama).
Dari segala isu, Saya (baca: hanya Saya secara pribadi, dalam hal ini Meidiawan Cesarian Syah) menarik isu paling tegas yang dimainkan di bawah sana adalah isu Agama: Bahwa sudah seharusnya muslim memilih kawan muslimnya, jangan yang non muslim (saya menulis “non muslim” karena kata-kata ini yang beredar).
Saya merasa penghembusan isu ini adalah sebuah kemunduran demokrasi yang melebihi tapal batas. Isu tersebut, memecah belah mahasiswa STAN menjadi dua kubu: Muslim dan Non Muslim. Isu semacam ini tidak hanya sensitif, tapi mengancam kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin di STAN selama ini.
Pendikotomian mahasiswa menjadi dua sisi dalam bentuk apapun: Muslim-Non Muslim, Lama-Baru, Akuntansi-Pajak, dan lain sebagainya cenderung mendegradasi akal pikiran yang seharusnya setia pada keadilan dan keluhuran berpikir. Ingat idiom paling lantang yang pernah dikeluarkan oleh George W. Bush? “You either with Us or against Us”. Seakan mahasiswa “dipaksa”memilih sisi jalan untuk diperhadapkan dengan sisi jalan lainnya. Seakan-akan pilihan yang diambil memiliki konsekuensi yakni menegasikan pilihan lainnya. Jika kamu tidak bersama kami, maka kamu memilih sebagai lawan kami. Satu pilihan yang menghilangkan pilihan yang lain.
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah miniatur Indonesia, dengan keberagaman sebagai nafasnya. Jika kita tersadar bahwa pijakan kita adalah keberagaman, mengapa kita melulu dicocok paksa dengan prinsip keseragaman? Senaif itukah kita? Untuk menjawabnya Saya lagi-lagi harus mengulik perkataan Gus Dur yang berbunyi “Tidak penting apa agamamu ataupun sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik kepada semua orang, orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu”. Di lingkungan seberagam ini, mengais keseragaman untuk diletakkan di atas keberagaman menjadi belati yang sewaktu-waktu justru bisa menikam pemiliknya sendiri.
Dalam debat, ada sebuah jenis kesesatan berpikir (logical fallacy) yaitu Argumentum Ad hominem. Ad hominem membantah fakta-fakta dengan merujuk kepada subjek yang membawa paham tersebut, bukan objeknya. Agaknya Saya harus mewanti-wanti agar mahasiswa STAN tidak masuk ke dalam lingkaran kesesatan berpikir ini. Seperti kutipan oven news di awal surat ini, saya berharap teman-teman memenuhi hakikat sebagai seorang intelektual. Seorang yang berpikir kritis dan cerdas dalam menggali program, nilai, serta misi seraya tidak berkutat pada pribadi semata.
Konstitusional Indonesia didirikan di atas lantai Pancasila. Hak konstitusional setiap warga negara dijamin setara untuk memilih dan dipilih dalam pemerintahan, termasuk di kampus. Saya percaya bahwa seorang pemimpin ditakdirkan untuk berdiri di atas semua golongan, di atas semua suku, dan di atas semua agama. Saya percaya bahwa pemimpin wajib memiliki ideologi yang bukan hanya tidak membeda-bedakan, namun juga wajib merangkul, menggandeng, lalu mengajak berjalan bersama. Pemimpin bukan memberikan pilihan antara Ya atau Tidak, melainkan memberi kertas kosong yang bisa diisi beraneka rupa jawaban serta mampu memerdekakan suara-suara. Baik suara-suara yang mendukung maupun suara-suara yang menghakimi.
Saya berharap, teman-teman mahasiswa memiliki refleksi mendalam untuk mengukur kapasitas seorang pemimpin dalam menentukan arah perjuangan kampus ini nantinya. Jika kita memang berada pada pijakan yang sama yakni keberagaman, maka sudah barang tentu pilihan yang kita ambil melepaskan segala unsur-unsur yang berpotensi memecah belah tersebut
Di luar segala anasir dan argumen yang sudah saya paparkan, Saya berada di haluan yang mempercayai bahwa seseorang yang mampu berdiri di atas segala golongan dan menjadi seorang “Ibu” yang tidak membeda-bedakan “anaknya” lah yang mampu menjadi pemimpin. Dalam hal ini, tentu Saya sudah mengambil pilihan bagi saya.
Jika kepemimpinan ditentukan dengan kemampuan menggandeng, ragam program, pengalaman di medan yang sama, serta kemampuan komunikasi tentunya bukan hal sulit bagi Saya untuk menentukan pilihan. Misi untuk mengetengahkan pembangunan manusia (baca: mahasiswa) juga dapat terbaca melalui program-program yang dipaparkan dengan nyata dan realistis.
Salah satu pilar demokrasi modern adalah meritokrasi, yaitu menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang memiliki kemampuan. Sudah saatnya kita bersandar pada sistem meritokrasi setelah politik dagang sapi terbukti hanya menguntungkan sebagian orang. Politik bagi-bagi kekuasaan hanya akan mendekonstruksi demokrasi yang sudah terbagun utuh di STAN ini. Meritokrasi dapat diwujudkan jika presiden mahasiswa-wakil presiden mahasiswa ini berani membuka sistem lelang jabatan sejak level Menteri BEM. Sistem lelang jabatan tentu saja memberikan kepercayaan lebih bagi saya untuk memilih karena sistem lelang jabatan meninggalkan sistem kartel atau politik dagang sapi yang merupakan penyebab bobroknya pemerintahan. Saya sangat menyayangkan apabila praktek bagi-bagi kekuasaan kepada para pengusung sudah dilakukan di usia semuda ini. Sikap ini akan menjadikan kita sebagai makhluk transaksional, pamrih, dan menggerus rasa ikhlas, nilai dasar kemanusiaan yang ada di dalam diri. Politik transaksional hanya akan mengakomodasi kepentingan yang seragam, bukan yang beragam.
Dengan besarnya nafas keberagaman tersebut, Saya yakin tidak ada yang terceraikan dengan hadirnya sosok pemimpin yang kita pilih apabila kita memang berpikir dengan meniadakan perbedaan-perbedaan. Karena menurut Saya, siapapun pemimpinnya, dia harus mampu menghadirkan KM STAN yang gilang-gemilang dan dibangun dengan bergotong-royong, bukan beromong kosong.
Tapi, Saya kembalikan pilihan kepada kalian, para mahasiswa. Di saat mentari masih belum merenta, dan malam belum menua, tentukanlah pilihan kalian. Saya hanya berharap; semoga kita masih dikaruniai rahmat untuk selalu bersikap adil sejak dalam pikiran.
Salam Saya untuk Keluarga Mahasiswa STAN yang adil dan tidak pernah membeda-bedakan
Meidiawan Cesarian Syah
————tanpa jabatan———-
————-tanpa warna———-
L’etranger: Sang Liyan
March 16, 2014 § Leave a comment
(Resensi buku Orang Asing karya Albert Camus)
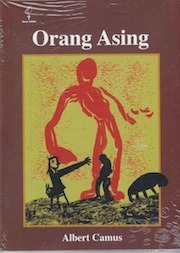
“Supaya semua tereguk, supaya aku tidak merasa terlalu kesepian, aku hanya mengharapkan agar banyak penonton datang pada hari pelaksanaan hukuman matiku dan agar mereka menyambutku dengan meneriakkan cercaan-cercaan.”
Kalimat sangat satir dan menggambarkan destruktivitas sekaligus konstruktivitas sebuah perasaan seorang terpidana mati tergurat lembut di halaman terakhir buku ini. Selarik kalimat tersebut juga menjadi senjata pamungkas yang tepat dalam fitrahnya sebagai representasi novel “Orang Asing” ini secara utuh. Rangkaian kata-kata tersebut nampak asing dan mengemukakan sebuah sikap yang teralienasi dan berada jauh dari tapal batas yang dibentuk oleh persepsi kewajaran. Berdasarkan basis itu pula, Camus mengintisarikan sebuah kisah yang ekletik dengan poros sebuah benda abstrak yang terus dipertanyakan: kebenaran. Camus mengetengahkan seseorang tokoh yang tidak hanya liyan, tetapi betul-betul berusaha menjalani ke-liyan-an yang wajar dalam institusi hidupnya. Penahbisan tokoh utama bernama Meursault dalam gelanggang hidupnya menjadi sentral dan menarik untuk ditelisik lebih dalam, terutama dalam kacamata eksistensialisme.
Saya mengutip Jeannyves Guerin dalam pernyataannya bahwa dalam pandangan pendekatan moral-filosofis, Albert Camus “hanya dapat dimaknai secara utuh apabila kita mengetahui eksistensialisme.” Berpijak pada remah frase tersebut, karya monumental Camus ini harus dibaca dengan mengenakan kacamata eksistensialisme. Jika tidak, rangkaian kata yang kita kunyah hanya sebuah kehambaran. Kita hanya akan membaca catatan harian seorang yang aneh dan tragik, tanpa mengetahui hakikat yang berperang di dalamnya.
Eksistensialisme memandang manusia sebagai sebuah institusi yang sadar akan dirinya. Ketersadaran itu membuat ia bisa berada di dalam diri sekaligus ada di luar dirinya (terutama dalam kaidah penilaian diri). Pemosisian diri seperti ini membuat manusia seperti makhluk terbatas yang dihamparkan di padang ketidakterbatasan kehidupan. Keterbatasan yang dikepung ini menjadi pangkal dari penafsiran diri menjadi sesuatu yang sia-sia jika dimaknai. Tiap usaha manusia menakrifkan kehakikian hidup digiring menuju ambang kegagalan. Karena batas yang ada pada manusia tidak mampu memenuhi relung ketidakterbatasan nasib kehidupan. Akhirnya yang dirasakan hanya perspektif ketanpaartian, tanpa tujuan, tanpa arah, dan pertanyaan akan hidup yang takkan pernah selesai.
Kebenaran, sebagai poros dari jenis pemahaman ini menjadi sebuah hasil doktrinasi yang didekonsktruksi. Mudahnya, ia dipecah menjadi puing-puing yang lebih bias di mana setiap puing dipertanyakan hakikatnya. Puing tersebut tidak bisa dipaparkan secara hitam putih. Eksistensialisme menolak kebenaran mutlak. Tiada kebenaran yang hakiki yang lahir karena doktrin. Manusia dianggap sadar sehingga mereka mampu menentukan kebenaran hakikinya. Oleh karena itu, Kierkegaard, bapak eksistensialisme, menulis diri manusia sebagai objek sekaligus subjek kehidupan secara kontinu. Kebenaran tidak disimplifikasi dari hasil konsensus masyarakat, namun harus ditemukan dan dijalani. Di salah satu tulisannya, Kierkegaard menulis “the highest and most beautiful things in life are not to be heard about, nor read about, nor seen but, if one will, are to be lived.” Hal paling asasi dari kehidupan lahir jika manusia menjalani hidupnya sendiri.
Dalam “Orang Asing”, Meursault digambarkan sebagai manusia antinorma -bahkan di dalam sebuah dialog, ia dicap anti Kristus – yang menjalani hidup wajar (menurut cara pandangnya) namun aneh (jika dihadapkan pada konsensus umum). Pada awal novel, deskripsi tersebut telah hadir dan berbunyi:
Hari ini Ibu meninggal. Atau, mungkin kemarin, aku tidak tahu. Aku menerima telegram dari panti wreda: “Ibu meninggal. Dimakamkan besok. Ikut berduka cita.” Kata-kata itu tidak jelas, mungkin ibu meninggal kemarin.
Aposisi kalimat ini secara liar mempertanyakan kehidupan seorang anak yang seakan melupakan ibunya dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Meursault acuh atas kematian ibunya, dan terlihat tidak peduli akan nasib ibunya hingga persoalan meninggal kemarin atau kemarinnya lagi tidaklah begitu penting. Dalam keberlanjutan kisahnya, Meursault digambarkan lebih liyan. Ia tidak menangis saat pemakaman ibunya, berhubungan dengan kekasihnya tepat sehari setelah pemakaman, dan lebih sibuk mengomentari kecapan-kecapan penghuni panti jompo dibandingkan mengurus jenazah ibunya. Tapi Meursault juga satir dalam kalimatnya, “Aku bahkan mendapati kesan bahwa jenazah itu, yang terbaring di tengah mereka, tidak mempunyai arti apa-apa bagi mereka.” Padahal, dalam ruang duka, Meursault sendiri tidak menangis – yang menyebabkan kita berpikir, jangan-jangan jenazah Ibunya pun tak berarti bagi dirinya -.
Camus kemudian menggambarkan liku hidup Meursault menjadi rangkaian yang banal: menolak pernikahan sebagai sebuah lembaga dan memandangnya sebagai ritus belaka (Ia mengafirmasinya dengan janji mengatakan “iya” pada siapapun wanita yang mengajaknya menikah), hidup bersisian dengan orang-orang yang sinting (Salamano tua yang sadis pada anjingnya atau Raymond yang seorang germo), serta melakukan pembunuhan sadistik (tetap menembaki orang yang telah dibunuhnya sebanyak empat kali).
Protogoras menciptakan istilah homo mensura, yaitu manusia sebagai tolok ukur. Dalam eksistensialisme absurditas ala Camus, tolok ukur manusia lahir dari kegagalan inheren manusia untuk memahami hidupnya. Akibatnya, hidup dijalani secara absurd sambil menuju pada satu kepastian mati dan tolok ukur tadi menjadi tidak pasti pula. Melalui bibir Meursault, absurditas ini tergambar jelas ketika ia sendiri menggambarkan kematiannya dengan kata-kata “Pada hakikatnya aku tahu bahwa mati pada umur tiga puluh atau enam puluh tahun tidak begitu penting, karena tentu saja dalam kedua kasus itu laki-laki dan wanita lain akan tetap hidup, dan itu terjadi selama ribuan tahun.” Iya, kematian didefinisikan menjadi variabel tanpa peubah, di mana tidak akan terpengaruh atau mempengaruhi kematian orang lain. Dalam falsafah ini, tolok ukur menjadi bukan hanya “tidak pasti” melainkan “tidak penting”. Setiap manusia bisa membuat tolok ukurnya sendiri.
Tentu saja benturan laku Meursault dengan kenyataan hidup menjadi akhir yang sempurna dalam novel ini. Kejahatan pembunuhan yang diseret di depan muka persidangan menjadi apik ketika Meursault dalam kesadarannya membantai sikap hidup yang tragik sekaligus nostalgik. Ia merekonstruksi sisa-sisa harapan yang dimiliki menjadi bangunan utuh tempat ia berlindung. Meursault menjadikan dirinya objek yang sanggup menjalani ketidakbiasaan menjadi sebuah kebiasaan. Ia menolak pengakuan dosa dan memilih menikmati waktu yang tersisa sebelum dihukum mati.
Meursault dianalogikan sebagai tokoh Sisifus yang mendorong batu ke atas bukit untuk hanya melihatnya menggelinding kembali ke bawah kembali dalam sebuah hukuman yang abadi (Hal ini tercermin dalam kumpulan esai Cerita Sisifus, juga karya Camus). Hukuman yang merepresentasikan kesia-siaan. Di padang kesia-siaan yang begitu luas, Camus lewat Meursault mengambil sudut pandang berbeda. Ia menggamangi sebuah harapan, di mana ketika Sisifus turun setelah mendorong batu ke puncak bukit, ada harapan agar batu itu tidak menggelinding kembali ke bawah. Harapan semacam ini yang dieksploitasi oleh Camus lewat penggalan renungan Meursault: “Kita selalu membayangkan secara berlebihan sesuatu yang tidak kita ketahui.” terkait dengan “…aku melihat bahwa yang tidak sempurna pada pisau pemenggal, adalah bahwa tidak ada kesempatan, sama sekali tidak ada.”. Ya, dalam keterperaman luka yang sejati pun manusia masih mencari kesempatan akan adanya harapan.
Maka, sejatinya hidup dalam perspektif L’etranger adalah hidup yang liyan: berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Meursault adalah orang yang memandang kehidupan sebagai, mengutip kata-katanya sendiri, sebuah pintu kesengsaraan. Absurdisme memandang kematian sebagai sebuah pembebasan. Dalam “Orang Asing”, kematian justru dirayakan sebagai sebuah persiapan untuk hidup kembali. Hidup dari kesengsaraan mati di dunia. Perihal yang menjadi suatu oposisi sempurna dari sebaris sajak Chairil : Hidup hanya menunda kekalahan. Mungkin Meursault justru akan mendatangi Chairil dan berucap: “Tidak ada yang kalah dalam hidup, seperti halnya tidak ada yang menang, Ril. Hanya kematian yang sepenuhnya datang menghampiri.”
Meidiawan Cesarian Syah
…..I owe to my angel mother
December 21, 2013 § Leave a comment
Tiada kata-kata yang mampu menerjemahkan maaf atas luka yang pernah saya goreskan kepada Ibu. Jika maaf Ibu tidak bertepi, beribu dusta yang berulang bukankah jadi tidak berarti? Tidak seperti cermin, Ibu tidak pernah membalas tuba dengan tuba. Ibu terlalu sibuk menganyam cinta lewat air mata-air mata kita. Walau saya juga yakin, ada air mata Ibu yang tersulam di sana. Sebuah kain kasih sayang dianyam dengan air mata, lalu dikenakan kepada anak-anaknya. Lebih hangat daripada baju dengan merk apapun di toko-toko ternama
Ibuku, adalah perempuan yang melahirkanku lewat gua garba. Ibuku, perempuan yang mengenal aku lebih lama, jauh lebih lama dari orang-orang lain. Aku pernah hidup dalam raganya. Ibu adalah duniaku sebelum aku mengenal dunia. Hanya lewat senyum Ibu, aku merasakan gerbang rumah terbuka. Laiknya senyum seorang Ibu siap menerima anak-anaknya yang kotor dan berlumuran dosa purba.
Ibu, jika suatu saat aku lupa mengabarimu. Aku mohon maaf, mungkin karena teman-temanku yang berusaha menghadiahkanku nuansa rumah saat di dekat mereka. Padahal suara ibu adalah rumah tempat rinduku dapat benar-benar pulang. Kita lebih butuh rumah daripada sekedar nuansanya bukan? Maafkan aku Ibu, rindu ini masih terlalu lupa tempatnya pulang.
Ibu, maafkan aku melupakan pertaruhanmu dengan kehidupan untuk memberiku kehidupan. Begitu dekat setiap nafasmu dengan kekalahan, tapi kau tidak pernah menghirupkan kekalahan itu padaku. Kekalahan bukan pilihan untukmu. Terbelahnya tubuhmu, derasnya kucur darahmu, rintihan nyeri yang sambung-sinambung adalah restu yang kau berikan untuk hadirku. Dan kemenanganku atas nafas pertama, adalah rangkaian kekalahan kecilmu pada tubuh dan kesakitannya.
Aku kau ajari berkata dan berbahasa. Engkau menyuapiku huruf demi huruf, meletakkannya di gigir lidahku yang lunak dan kelu. Kau habiskan seharian untuk membuatku dapat membedakan “A” dan “U”. Dasar waktu yang pencemburu dan cepat sekali berlalu, aku cuma bisa mengikuti dengan menggugah tangis dan sedu. Kau menyimpulkan senyum, membasuh air di jelaga mataku. Hidup bukan masalah A dan U saja, katamu. Aku dipeluk, dimandikan dengan doa nun haru.
Lalu ketika aku bicara, sudahkah aku memenuhi kehendakmu untuk bisa bercakap-cakap? Atau kusia-siakan kata-kataku untuk mereka yang bukan kau? Ah, Ibu. Untaian kata-kata yang pernah kau ajarkan bahkan jarang aku gunakan untuk menyapamu, apalagi berdialog. Beruntunglah mereka yang sering berdialog dengan Ibunya. Karena pada saat itu, deburan kata-kata dari lidah yang basa, seakan bergelombang menuju pantainya. Kesabaranmu adalah lentera, dan aku bisa membaca dunia karenanya.
Ibu tidak pernah menolak pintaku. Bumi pun bisa Ibu susuri, bukit dan lembah juga bisa Ibu langkahi. Ibu, bolehkah aku meminta pelangi Engkau pintalkan juga di langit sana? Ketika kanak-kanakku meminta, Ibu membuat Tuhan cemburu. Tuhan lah yang melukis pelangi di kanvas senja, Nak. Ah, Ibu tidak tahu, kadang peluhmu juga bisa berujung pelangi, Bu. Aku ingin pelangi yang itu saja.
Ibu, masihkah membacai buku-bukuku seperti dulu? Buku yang berisi keangkuhan dan keegoisanku menuntut ilmu. Ah Ibu, jangan terlalu kau seriusi buku-buku itu. Kau memiliki ilmu yang semesta sendiri menuliskannya pada sekujur lengan dan langkahmu. Dan Ibu, engkau adalah bacaan yang tak terbaca, sebuah amal yang mulia mengalir di tajamnya usia. Ibu adalah seuntai kata yang tak terucap.
Surat ini aku tulis di pucuk malam yang sunyi. Aku mengingat Ibu yang merenta, menua, dan melihat anak-anaknya dewasa. Ibu yang kini hanyalah muara dari sisa-sisa cinta. Ibu masih rajin menganyam kah? Dari sisa-sisa cinta itu masih bisa menjadi sebuah pakaian kasih sayang kah? Masih boleh kukenakan kah, Bu?
Ibu, terimalah sujud maafku. Aku hanya bisa mengecupmu lewat doa-doa. Aku hanya bisa menghamburkan cintaku padamu lewat kata-kata. Izinkan aku mencium surga-surga di telapak kakimu, Bu. Klisekah jika aku menyatakan: “Aku menyayangimu, Ibu”.
Kalimat itu berisi sisa cintaku yang utuh, Bu….tak terbagi…..
P.S.:
untuk Ibuku, Zahratul Wardah
anakmu
Meidiawan Cesarian Syah
Quote yang menginspirasi tulisan ini
“All that I am or ever hope to be, I owe to my angel mother.”
― Abraham Lincoln
Bagiku ibuku adalah Nilai tanpa Sumpah! Api tanpa Debu! , sekiranya ia hidup barang tujuh abad yg lalu dan sekiranya aku seorang raja seperti Sri Kertanegara, iapun akan aku candikan, dan aku persembahkan gelar Pradnya Paramita, Dewi Kebijaksanaan Tertinggi, yang di persembahkan oleh Kertanegara pada Ken Dedes
—-Pramoedya Ananta Toer
Di Ujung Roda Reformasi
December 19, 2013 § Leave a comment
Pergolakan sebuah masa acapkali didendangkan lewat langgam yang berupa-rupa. Ada kalanya ia dinyanyikan dengan senjata, ada waktunya ia disenandungkan lewat kata, dan ada saatnya ia diperam dengan kesenyapan nun basa. Namun tembang apapun yang dilantunkan, pemuda selalu memosisikan dirinya menjadi seorang konduktor: arsitek atas nasib orang-orang sekeliling. Melodrama perjuangan dijejali manusia muda sebagai bintang di panggung pementasan. Kerjap lilin perubahan dinyalakan dengan asa yang menggantung berbahan bakar darah, keringat, dan air mata. Jikalau mesin perubahan bangsa dinyatakan bergerak, pastilah pemuda ada di poros tiap rodanya. Rimbunan semangat, oleh mereka diputar dan digulirkan demi translasi keburukan jaman menuju suatu kebaikan. Drama kehidupan yang dewasa ini diperankan oleh aktor bernama: mahasiswa.
Di ujung usianya, serangkai kata-kata bermuara di bibir Pramoedya Ananta Toer. Rangkaian kata yang keluar dari penulis garda depan Indonesia itu kelak dipahat pula pada nisan tempat beliau disemayamkan kekal di Karet Bivak. “Pemuda harus melahirkan pemimpin”, kalimat itu berjejer dalam kokohnya, menjelma sebagai sebuah lirih yang abadi. Pesan beliau memang singkat, namun cara penerjemahan frase ini tidak akan selesai hingga kapanpun. Kata-kata itu akan selalu menjadi pengingat, bahwa di masa apapun akan ada keharusan bagi golongan pemuda untuk berada di garis depan dan menjadi pemimpin.
Keterikatan antara kemepimpinan-kepemudaan ini bagaikan kereta nasib yang menggelinding di atas rel masing-masing takdir manusia. Mereka tidak saling bersinggungan. Tapi kadang, laiknya gerbong kereta, ia mengangkut nasib-nasib yang menuju stasiun yang sama. Mereka memercayakan dirinya dibawa oleh sang masinis kehidupan. Soal kereta akan tiba pukul berapa adalah pertanyaan kesekian dari hidup yang dipertaruhkan. Dan pemuda, sekali lagi, seringkali dipercaya mengemban amanat untuk menjadi sang masinis dari waktu ke waktu.
Sebaik-baik pemuda adalah pemuda yang betah berlama-lama dengan proses pendidikan. Pendidikan adalah pangkal dari pengetahuan, dan pengetahuan, meminjam kata-kata Plato, adalah asupan jiwa (food of the soul). Mahasiswa ialah perwujudan nyata di mana idealisme masa muda bertemu rasa ingin tahu, kepedulian sosial, dan kemurnian intelektual. Soe Hok Gie, dalam catatan hariannya menulis bahwa mahasiswa adalah happy selected few. Mereka adalah kaum yang beruntung dapat berbulan madu dengan manisnya pendidikan dan karenanya harus menyadari serta ikut dalam perjuangan bangsanya.
Teorema Soe ini menjadi menarik mengingat kelahiran Indonesia dari gua garba kemerdekaan tidak lepas dari peran para mahasiswa, the happy selected few. Politik balas budi berupa edukasi yang ditanamkan Hindia Belanda dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para intelektual muda untuk menguras ilmu dan membentuk jatidiri mereka menjadi pemuda yang sadar. Ketersadaran itu diejawantahkan lewat sintesis pendidikan-politik dan ditunjukkan lewat kegiatan utamanya: mengganyang kolonial. Mereka ini yang bermula-mula terjun ke lembah politik yang dipenuhi lampu-lampu yang kotor. Tak ada ragu dari sudut hati mereka untuk menghadapi kekuasan yang lebih besar dan tiran sekaligus musykil untuk digulingkan. Walau mereka tahu, perlawanan kekuasaan tak mengenal tapal batas antara keberanian dan kematian.
Memoar paling saya ingat dari Bapak Politik Etis, Mr. Conrad Theodore Van Deventer adalah sebuah kalimat lembut berbunyi, “Het wonder is geschied, Insulinde, de schooner slaapster, is ontwaakt.”. Terjemahan bebasnya kira-kira, “Suatu keajaiban telah terjadi, Insulinde (istilah nama Indonesia tempo dulu), puteri cantik yang tidur itu, telah bangkit”. Kalimat itu ia tulis di majalah De Gids pada tahun 1908 kala ia menyaksikan kebermulaan pergerakan nasional dari sekolah dokter gubermen bernama STOVIA. Mahasiswanya mendirikan organisasi yang namanya lestari hingga kini: Budi Oetomo. Di luar pragmatisme kesukuan Budi Oetomo itu sendiri, dari STOVIA lahir mahasiswa yang keras menentang pemerintahan kolonial dan lebih berwawasan nasionalisme utuh seperti Suwardi Suryaningrat dan dr. Cipto Mangunkusumo.
Sejenis perlawanan juga terjadi di Belanda dan bergerak secara paralel dengan tokoh utamanya Mohammad Hatta. Ia membentuk Indische Vereeninging yang kemudian berubah nama menjadi Indonesische Vereeninging pada tahun 1922. Perlawanan total sudah ditancapkan Hatta sejak ia memilih nama organisasi. Hatta jelas-jelas paham bahwa ia memakai sebuah nama yang menjadi cikal bakal nama negara dan menolak atribusi kebelanda-belandaan. Nama Hindia Belanda ia lupakan, ia coret tegas dan mengambil nama Indonesia dibandingkan label penjajahan tadi. Indische Vereeninging yang diprakarsainya semula merupakan sebuah kelompok diskusi mahasiswa di Belanda. Ketika himpitan kolonialisme makin meluruhkan rasa adil, orientasi perhimpunan ini bergeser dan memilih jalur politik. Tujuannya tak lain: ihwal memiliki negara Indonesia yang merdeka.
Moda translasi dari diskusi menuju revolusi sudah bukan hal yang aneh lagi. Sejak Plato mendirikan Hekademos – yang nantinya berubah menjadi Akademi lalu menjadi Universitas – pemuda memang diserahkan kepada negara untuk dididik pemikirannya. Seni berpikir dilatih lewat gaya kritik spontan ala Socrates. Diskusi dilakukan untuk mengasah pikiran. Sebilah pikiran yang tajam, mampu mengoyak penjara jenis apapun. Akhirnya, tidak ada penjara bagi pikiran di sana. Dengan demikian, argumen akan terlatih dan orang mampu memilih posisi strategis atas kritisisme yang murni, tanpa tumpangan apapun.
Di lain hal, gugusan kritik harus tepat sasaran. Mahasiswa harus memilih basis yang tepat untuk dibawa kepentingan politiknya. Rakyat adalah sebuah keputusan paripurna dari inti persoalan ini. Suara keberpihakan selain kepada rakyat lebih baik disunyikan, dibekap, lalu ditenggelamkan dalam palung tanpa dasar. Menurut saya, niat semacam itu bahkan menjadi antipoda terhadap seni berpikir. Ia mengkhianati proses pemurnian pikiran yang terintegrasi langsung kepada hati. Jika permasalahan rakyat sudah bukan menjadi inti nurani, lalu apa gunanya mahasiswa mengambil preposisi untuk mengabdi?
Preposisi itu tidak sekedar menjadi oposisi setiap kebijakan pemerintah saja. Apabila sikap pemerintah dianggap koheren dengan kebutuhan masyarakat, mahasiswa bisa menjadi titik tengah yang membantu pendelegasian intensi pemerintah terhadap rakyat. Sikap ini, tidak lain pasti menimbulkan kemesraan antara mahasiswa dan pemerintah, dan hal ini sangat mungkin untuk terjadi.
Medio 1966-1971 merupakan era romantisme mahasiswa dengan pemerintah. Mahasiswa menyelaraskan harapan dengan adanya pemerintah baru. Diawali proses “penyucian” sejarah lewat pagebluk Gerakan 30 September, mahasiswa lalu berlaku seperti seorang mesias: pembebas angkara murka. Mereka ikut dalam penumpasan orde lama serta turut dalam prosesi pemakamannya. Tidak hanya itu, mereka juga mengambil sendiri haluan politiknya untuk masuk dalam pemerintahan. Agen-agen mahasiswa yang masuk ke dalam pemerintahan ini menjadi penyambung lidah mahasiswa yang lebih muda. Celakanya, mereka yang berada di posisi pemerintah mulai bergeser dari nurani murninya: nurani kepada rakyat. Kemesraan itu pun akhirnya kandas. Mahasiswa muda menolak menyandera nurani dan memilih berhadapan dengan tiran yang lain.
Sayangnya, pilihan sikap ini tidak disertai dengan metode turun ke bawah menjemput kehendak rakyat. Mahasiswa bersikap elit, dan gagal mengajak rakyat yang nuraninya mereka wakili untuk turut serta melawan. Mereka juga terlalu bersikap etnografi dan hanya terpusat di Jakarta saja. Apa daya, rakyat tanpa sokongan pun beringas dengan sendirinya. Peristiwa petisi 24 Oktober lalu Malari berakhir pada radikalisme massa. Kerusuhan yang terjadi pada periode 1971-1974 justru menerbitkan luka baru bagi idealisme mahasiswa. Idealisme itu akhirnya dicokok penguasa untuk dipasung di dalam kampus. Komandan gerakan ditangkapi dan dipenjarakan. Gerakan mahasiswa dipalugodam dan berhenti.
Empat tahun kemudian, gerakan mahasiswa kembali mengobar di Bandung dan Yogyakarta. Mereka mengecam perpanjangan rezim dengan pencalonan kembali presiden yang sama. Presiden yang telah menjadikan kebebasan berpendapat seperti hewan ternak: digembalakan dan dikandangkan. Presiden yang menjadikan pilihan untuk menyembelih, laiknya pada hewan ternak, etika berpendapat yang sudah dianggap keliru. Pengecaman ini tidak lama, setelah rezim represif ini mengeluarkan senjata paling kuatnya bernama tentara. Kampus dikepung, dan mahasiswa dipenjara baik jiwa maupun raganya.
Tak cuma gagal, perlawanan mahasiswa bahkan ditumpaskan hingga akar-akarnya. Perpindahan jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke tangan Daud Joesoef, mengakibatkan keluarnya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)/ Badan Koordinasi Kampus (BKK) melalui SK No.0156/U/1978. Kebijakan ini mengebiri semangat mahasiswa hingga titik terendah dan menjebloskan mahasiswa kembali ke konsep angka-angka. Mahasiswa diproyeksikan untuk fokus ke dalam kegiatan akademik dan dinilai hanya pada satu muara: Indeks Prestasi Kumulatif. Betapa sangat menyedihkan jika mahasiswa kini masih menganut fokus yang sama dan meninggalkan, mengutip Soe lagi, panggilan seorang pemikir. Keabaian atas realitas sosial sekitar, bahkan dicecar oleh Soe dengan kalimat: “Kelompok intelektual yang berdiam dalam keadaan yang mendesak telah melunturkan semua kemanusiaannya”.
Pelaksanaan kebijakan NKK/BKK ini bahkan mengamanatkan wewenang kekuasaan kepada rektor dan pembantu rektor untuk menentukan kegiatan mahasiswa, yang menurutnya sebagai wujud tanggung jawab pembentukan, pengarahan, dan pengembangan lembaga kemahasiswaan. Dengan pemberangusan seperti ini, mahasiswa kembali ke dalam idiom kupu-kupu (kuliah-pulang kuliah-pulang). Kehalusan budinya tidak pernah terlatih.
Periode setelahnya, Dewan Mahasiswa, yang mengorganisasi pergerakan dimandulkan sekaligus dibubarkan. Mahasiswa diceraikan dengan politik praktis. Suara dari kampus hanyalah melodi kebisuan yang sempurna. Suara mahasiswa nyenyak dalam buaian Sistem Kredit Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif. Ketika Mendikbud kemudian dijabat oleh Nugroho Notosusanto, rezim bergerak lebih keras. Pemerintah memberlakukan depolitisasi, kegiatan mahasiswa di luar akademis disalurkan lewat lembaga kemahasiswaan formal seperti Senat Mahasiswa [Sema], dan Badan Eksekutif Mahasiswa [BEM]. Di luar itu dianggap ilegal.
Masa-masa ini adalah masa paling kelam dalam roda pergerakan kemahasiswaan di Indonesia. Jangankan memilih haluan politik, mahasiswa hanya dijadikan sebuah “buku”. Mereka tak lebih dari manusia yang hanya mengulang-ulang secara presisi apa yang ditulis dalam diktat-diktat, manusia yang penuh hafalan kesimpulan, manusia yang bicara tapi lidahnya dirantai. Dan seperti halnya sebuah buku, sebaik apapun ia hanya sebuah benda. Dan sebaik-baiknya benda, ia bisu dan tak bisa bermanfaat tanpa sebuah subjek yang menggunakannya.
Pendidikan di masa ini justru menjadi senjata yang tumpul. WS Rendra dalam sebuah puisinya juga mempertanyakan pendidikan jenis ini, sebuah sistem pendidikan yang kaku dan membelenggu:
Apakah gunanya pendidikan
bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing
di tengah kenyataan persoalannya?
Apakah gunanya pendidikan
bila hanya mendorong seseorang
menjadi layang-layang di ibukota
kikuk pulang ke daerahnya?
Apakah gunanya seseorang
belajat filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran,
atau apa saja,
bila pada akhirnya,
ketika ia pulang ke daerahnya, lalu berkata :
“ Di sini aku merasa asing dan sepi !”
Jika pendidikan adalah senjata, maka kata-kata dan tindakan adalah kemampuan kita untuk mengayunkannya. Pendidikan adalah senjata yang bisa digunakan para intelektual untuk menghardik penindasan atas kaum yang lebih papa ilmu daripada mereka. Di saat seperti ini, kuasa atas ilmu dapat dimanfaatkan mahasiswa ketika mengambil sikap menentang pemerintah. Mahasiswa yang tidak memiliki kuasa atas ilmu yang cukup, lebih baik jangan berkacak pinggang ikut serta dalam reformasi dan revolusi peradaban.
Mahasiswa jenis ini adalah mahasiswa salon, sibuk memoles wajahnya dengan coreng moreng aksi. Tapi, aksi yang ada hanyalah suara-suara tanpa arti. Barisan kata-kata tanpa ilmu, yang sebenarnya juga bukan milik siapa-siapa, dibiarkan berjalan sendiri menggedor-gedor pintu masuk reformasi. Tapi kata-kata yang kosong ini bahkan tidak akan masuk ke dalam ruang tamu. Ia rapuh dan selalu menggigil kedinginan diterpa hujan kritik masyarakat sekitar.
Ujungnya adalah persemaian lagi bibit kebencian pada mahasiswa seolah mereka berjuang hanya untuk mengisi panggung-panggung eksistensi tapi tidak peduli, masyarakat mana yang seharusnya mereka wakili. Bahkan animo terburuknya adalah mereka tidak dianggap mewakili kaum masyarakat manapun.
Oleh karena itu sudah seharusnya mahasiswa berkaca pada pendahulunya. Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangoenkoesoemo, Moh. Hatta, Tirto Adhi Soerjo, dan beberapa nama lain lebih lama berkutat dalam majelis diskusi sebelum membuat aksi. Diskusi-diskusi ini jauh sebelumnya bahkan dilakukan filsuf-ilmuwan seperti Isaac Newton atau Rene Descartes. Idealisme intelektual mereka tumbuh besar di ladang diskusi sebelum dibawa turun ke medan mobilisasi. Pemikiran yang matang menghasilkan pula mobilisasi yang terarah, tidak serampangan, dan jauh dari sifat-sifat membahayakan.
Mobilisasi massa yang serampangan pernah dikritik keras oleh Tan Malaka. Ia menganggapnya sama seperti putch atau anarkisme. Dalam bukunya Aksi Massa, Tan Malaka jelas menahbiskan golongan orang yang melakukan putch ini sebagai “Gerombolan yang bisanya hanya membuat rancangan menurut kemauan dan kecakapan sendiri tanpa memedulikan perasaan dan kesanggupan massa. Ia sekonyong-konyong keluar dari guanya tanpa memperhitungkan lebih dulu apakah saat untuk aksi massa sudah matang atau belum. Dia menyangka bahwa semua lamunannya tentang massa adalah benar sepenuhnya.”
Konklusinya nyata, penentuan haluan politik harus didasarkan pada diskusi yang mendalam, paradigma ilmu yang kokoh, dan keteguhan independensi. Mahasiswa haruslah memiliki sikap politik yang tegas terhadap kebijakan pemerintah, seperti halnya Hatta, Suwardi, ataupun Cipto. Sikap politik yang dipilih juga definit: selaras atau berlawanan, linier atau konfrontasi. Mahasiswa bukan makhluk melankolis yang seiya-sekata tanpa dasar atau menjawab semua pertanyaan dengan nada pragmatis, bahkan apatis. Jawaban seperti itu adalah entitas kekanakan dan harus dibuang jauh-jauh.
Kisah Wardi menerbitkan pamflet Als ik een Nederlander was yang menghujam langsung ke jantung pemerintah kolonial adalah sebuah contoh nyata, bagaimana sikap pemuda yang linier dengan keberanian menimbulkan kekaguman yang luar biasa dari segala penjuru. Cita-citanya akan Indonesia merdeka dengan lantang ia serukan dengan pamflet sindiran walau pada akhirnya dirinya tak lepas dari dampak yang tertangguk, yaitu pembuangan. Setidaknya keberanian Wardi sudah dilandasi pemikiran luhur dan ia tidak pernah kecewa dengan efek yang diterimanya.
Di suatu kemarau ideologi yang menyelubungi jasad reformasi, mahasiswa masih diharapkan mampu mengemban perjuangan kritisnya. Jika partitur kehidupan hanya dapat dimainkan sekali, maka saya berkeyakinan bahwa usia muda adalah sebuah chorus: serangkai notasi yang memiliki tahta tertinggi dari sebuah lagu. Dan mahasiswa, tentulah menjadi dirigen dari notasi nasib kebangsaan tadi.
Seorang mahasiswa adalah pemuda yang dalam diamnya pun berpikir, dan dalam bicaranya ia bergerak. Pada suatu masa mereka adalah pihak yang pernah menggulirkan roda reformasi. Dan di masa sekarang, mahasiswa berada di ujung rodanya. Jika kita tidak meneruskan rotasi, roda pun berhenti dan nasib bangsa kembali kita serahkan pada tirani. Maka ambillah posisimu, posisi kita, sebelum luruh nilai-nilai kemanusiaan itu. Tolak segala pendangkalan paradigma berpikir ilmiah dan teruskan sebuah pengembaraan kalimat yang pernah dilafalkan garang oleh W.S. Rendra: “perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata”. Kita adalah tuan dari harapan-harapan kita sendiri.
Meidiawan Cesarian Syah
Menteri Seni dan Budaya BEM STAN 2013-2014
Prodip IV Spesialisasi Akuntansi Kurikulum Khusus
—————————————————————————————————————————————————————————
Tulisan ini diterbitkan di Warta Kampus STAN edisi 23/ Desember 2013
EKS(TAX)E
December 7, 2013 § Leave a comment
Ekstase adalah nomina dalam Bahasa Indonesia yang berarti keadaan di luar kesadaran diri, seperti (contohnya) orang sedang bersemadi. Jika diulik dari sisi lain, ketika manusia mengalami ekstase, mereka berada pada satu titik kebahagiaan saat sekresi endorphin membanjiri otak. Kalau Syekh Siti Jenar menyebutnya: manunggaling kawulo gusti. Sengaja saya menyisipkan kata pajak (tax) di tengah-tengah kata ini sembari menyoroti fenomena masyarakat Indonesia. Latar belakangnya adalah orkestrasi keengganan membayar pajak yang makin lantang dimainkan di mana-mana. Entah darimana mereka mendapatkan partitur-partitur bernada sama: “buat apa bayar pajak? toh akhirnya dikorupsi”.
Ditinjau dari aspek psikologis, sikap masyarakat ini tentulah wajar. Toh, wacana pemerintahan bersih juga masih jauh panggang dari api. Hingga sekarang, pemerintah masih bergulat dengan dosa lama: bocornya anggaran. Maka orasi klausa tadi, ”pajak yang akhirnya dikorupsi”, juga tidak selamanya salah. Argumen ini juga menjadi titik kritis yang akan selalu disorot, muaranya pastilah semakin menguatkan sikap minor dalam kepatuhan perpajakan. Meskipun demikian, nyatanya hampir di seluruh sudut dunia, tidak ada orang yang ikhlas membayar pajak. Warga negara Amerika yang kesadaran pajaknya tinggi pun berteriak protes ketika pajak yang mereka bayarkan malah dihamburkan untuk agresi militer ke Irak dan menganggap alokasi itu salah prioritas. Prototip ini tentu saja menang kelas dibandingkan sikap kritis masyarakat kita yang baru berkutat pada ketidakpercayaan pada institusi pengelola anggaran negara.
Persoalan mendasar ini tentu saja membuat kita kembali pada solusi awal: membangun kepercayaan pada institusi, baik pada institusi penghimpun maupun insitusi pengguna dana pajak. Maka, sudah sepantasnya kita ini bersolek dan narsis. Aparat institusi hendaknya sadar atas perhatian publik, serta mempersembahkan kinerjanya bukan atas nama nilai semata melainkan juga sebagai sebuah pose. Pose terbaik di hadapan sorotan mata publik. Jadi, kritik yang dilayangkan seyogyanya ditanggapi dengan parade pose-pose tadi yang telah direkam kacamata masyarakat, seperti prestasi yang baik menurut survey KPK dan pendapat dukungan integritas dari berbagai pihak.
Jikalau kita kembali menilik pada sisi psikologis tentang keengganan membayar pajak tadi, maka perlu sebuah awakening shock yang menyatakan bahwa sebenarnya pajak itu hal yang sangat dekat dengan keseharian kita. Agaknya, pajak dibenci karena masih terasa jauh dari masyarakat, tak kenal maka tak sayang. Saya sendiri sedikit menyayangkan berkurangnya tayangan edukasi perpajakan melalui media paling dekat yang menyentuh sebagian besar rakyat, yakni televisi. Iklan Direktorat Jenderal Pajak hampir tidak lagi tampil, kalah dengan kampanye calon pemimpin yang maju di pemilukada beberapa daerah. Padahal, eksistensi pariwara ini, jika dikemas dengan baik, mampu menarik simpati bahkan menyampaikan doktrin hingga menembus layar. Narasi lucu seperti kartun atau ikut menyusupkan edukasi pajak ke acara anak-anak juga bisa dibuat sebagai fokus kita terhadap future taxpayer. Istilahnya dalam pop culture yang cukup terkenal adalah tax for dummies. Tentunya acara tadi dibungkus dengan sifat ramah. Perlu diingat, melakukan branding bukanlah sebuah dosa dan bukan sebuah masalah walaupun sudah pasti branding terhebat adalah melalui attitude pegawai pajak itu sendiri.
Yang perlu digarisbawahi, segala upaya narsistik ini harus dilakukan secara persuasif dengan mengetengahkan wajib pajak sebagai obyek. Bukan memberikan dogma sanksi atau penganggapan bahwa pengemplang pajak adalah makhluk asosial. Citra yang dipertaruhkan terlalu mahal untuk poin seperti itu. Biarlah pelaku tax evasion ini cukup kita saja yang tahu mengenai pelaksanaan sanksi pidana dan penindakan hukumnya. Orang-orang saja masih apatis jika dihadapkan pada definisi pajak yang sederhana, apalagi dihidangkan aneka tindakan yang sifatnya sudah masuk ranah represif. Tidak ada salahnya juga kalau kita kembali menyentuh melalui penggugahan sifat dasar manusia,yang cenderung senang berbagi.
Dengan masyarakat sebagai obyek, secara otomatis nantinya segi narsis ini juga akan berkutat pada sisi pewartaan manfaat pajak secara keseluruhan. Nihil hasilnya bilamana ini dikerjakan tanpa pemantauan institusi pengguna dana pajak. Membangun negeri juga tidak bisa dilakukan secara parsial, bagus di satu sisi namun mengorbankan sisi yang lain. Ibaratnya adalah bagai sebuah keluarga yang disharmonis. Sikap pretensi terhadap penggunaan dana pajak hendaknya mulai kita singkirkan-jauh jauh. Jika penggunaan dana pajak salah, kita bisa ikut menggugat. Bukankah kita bisa menggugat dengan memposisikan diri sebagai wajib pajak? Kalau dibiarkan, apatisme tidak sadar ini juga mengakibatkan energi keburukan yang sudah terlanjur menjalar akan semakin luas. Sekali lagi, bukankah menegakkan kebaikan itu adalah kewajiban setiap orang?
Aposisi yang diceritakan tadi memiliki destinasi yaitu mampu menggugah kesadaran manusia untuk berbagi dalam perannya sebagai wajib pajak. Apabila penggunaan dana pajak sudah terasa sangat nyata, maka akumulasi sikap minor ini akan terkikis perlahan. Fenomena aktivitas membayar pajak sebenarnya mampu menjadi representasi wajah manusia selaku filantropis, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan berbagi. Bukan tidak mungkin gejala sebagian orang kaya di Amerika Serikat yang meminta dirinya dipajaki lebih besar dapat timbul di Indonesia. Eks(tax)e saya menyebutnya, berada dalam keadaan khusyu saat berbahagia melakukan pembayaran pajak. Sebuah perasaan yang abnormal sekarang, namun siapa tahu? Toh, hal yang pasti di dunia ini hanya ketidakpastian.
—————————————————————————————————————————————————————-
artikel lawas ini saya kirimkan untuk dimuat di Majalah Tugu Muda ketika masih menjadi Pegawai KPP Pratama Blora
Banjirkanal, Semarang di Hujankala
November 26, 2013 § Leave a comment
Hujan yang gugur dari kelopak langit
masih bersedia mengunjungi tidur mobil-mobil
yang lelap dalam senyap
dan bersenandung mengerami pahit lanskap
lalu luntur ke dalam parit-parit gelap
Sebuah jalan legam, ditaburi bulu-bulu debu
melingkari hutan baja
mengantar hulu kota
kepada hilir pantainya
Ufuk kota dan garis pantai berdiam dalam rimba
urat-urat metropolis benyanyi sunyi pada semesta
galur di topeng manusia
terbelah dan terkoyak
dibenam air mata
Langit menggoreskan senyum pada jembatan-jembatan penyeberangan
seorang penari, dengan topeng tanpa galur, memalsukan hujan sebagai kendang
yang mengiringi pembunuhan rasa bosan
barangkali ketika ia menyelipkan senyum di sela bibir
dengan gincu sisa kemarin, waktu bisa beranjak muda
dan kenangan kanak-kanaknya membiarkan tangisnya bertambah tua
anak-anak mesra di pinggir kali yang banjir
bercanda di gigir kanal tak bermuara selain pada keabadian yang ceria<
air menyelimuti tubuh mereka dan menajamkan luka di lutut-lutut usia
dalam surat yang dikirim kepada rahasia, hujan bersabda
“mereka menghuni surga, aku jaga mereka dari layunya nyawa”
anak-anak terus berjingkat, memainkan permainan tanpa aba-aba
memandikan hujan lewat ricik airnya
“hujan, jangan menangis saja,aku mandikan kamu sebelum terbitnya surya”
lalu berputar lagi di riuh senja, jalanan menulis nasib pengendara yang menua
hujan gugur di muara sebuah kota
menyenyakkan kepulan debu dan aspal di ujung sebuah lorong bernama rindu
merayu senja untuk segera tumbang pada pembaringan bunga-bunga nasib yang menguap
untuk gugur bersama hujan esok hari…
Tangerang Selatan, 14 November 2013